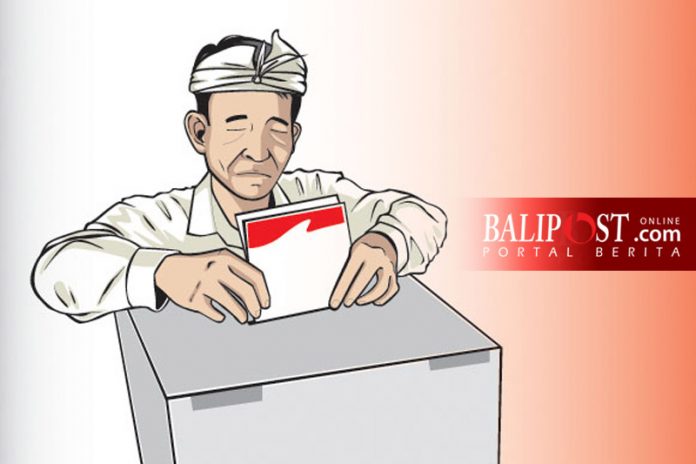
Oleh I Nyoman Dwi Rasnikal
Hari ‘’H’’ pemilu serentak bulan April mendatang, berbagai fenomena politik bermunculan dan menyebar di masyarakat. Ada yang mewajibkan pasangan calon presiden agar dapat membaca kitab suci. Sebelumnya juga ada yang mensyaratkan jika pasangan calon presiden dapat berbahasa Inggris.
Masing-masing tim sukses bereaksi terhadap usulan-usulan seperti ini. Mendengar hal ini ada yang lucu karena seolah mengada-ada dan saling balas. Setelah masalah kitab suci ini mendingin, muncul lagi fenomena politik lain. Ada hoax tentang tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos. Kontainer ini konon ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Masyarakat tertawa dengan fenomena politik ini. Bagaimana fenomena ini menggambarkan suasana politik di Indonesia saat ini?
Persoalan demikian sebenarnya sebuah kiat politik tradisional. Sangatlah ironis jika Indonesia yang dengan sadar memilih sistem demokrasi melalui reformasi tahun ke-2 ini. Dilihat dari jangka waktu reformasi tersebut, maka seharusnya saat ini gaya politik tradisional ini harus sudah ditinggalkan.
Mengapa dikatakan tradisional? Saling serang fisik itu merupakan cara paling mudah untuk menjatuhkan lawan. Seolah tidak mempunyai kreativitas untuk meningkatkan capaian prestasi.
Tuntutan untuk membaca kitab suci atau memakai bahasa Inggris, mungkin hasil intipan dari masing-masing pihak terhadap kelemahan lawan itu. Akan tetapi sebenarnya masih ada yang lebih bagus sebagai cara untuk meningkatkan elektabilitas.
Kalaupun harus berupaya ingin menunjukkan keunggulan atas lawan, maka yang mungkin lebih elite adalah dengan mengungkap rasionalitas program dengan data yang memungkinkan. Data inilah yang seharusnya ditunjukkan kepada masyarakat, kemudian dibandingkan dengan apa yang diungkapkan oleh kompetitor.
Menyerang kemampuan yang kiranya berjauhan dari persoalan kebijakan, sepertinya masih lemah. Kalaupun misalnya kompetitor tidak mampu berbahasa Inggris, tetapi sebagai presiden ia tetap akan mampu membuat keputusan politik.
Dapat saja dia memakai bahasa daerah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya juga demikian kalau dia tidak mampu membaca kitab suci. Kiranya cara untuk menyerang lawan politik tersebut hanya bersifat elementer saja.
Dari kacamata elite, seperti yang telah diutarakan tadi, usulan seperti ini kelihatan tidak mempunyai ide lain untuk mengatasi lawan. Tetapi harus juga dilihat bahwa di balik usulan yang elementer tersebut, ada hal besar yang mesti diperhatikan, yaitu kecenderungan memandang remeh kemampuan pengetahuan politik masyarakat.
Jika memang misalnya debat memakai bahasa Inggris dan kemudian kandidat tidak mampu melakukannya, diprediksi masyarakat akan menjauh dari sosok bersangkutan. Padahal belum tentu demikian. Demikian pula sebaliknya untuk yang tidak mempunyai kemampuan membaca kitab suci. Masyarakat dipandang rendah pengetahuan politiknya. Ini berbahaya bagi para calon.
Kecenderungan penyerangan secara tradisional ini dapat dijelaskan musababnya. Pertama, kedua belah pihak merasa kekuatannya hampir sama. Tetapi pada saat yang sama tidak mempunyai ide untuk mengatasi kompetitor dengan cara yang lebih baik.
Karena kekuatan merasa sama, maka mereka tidak mempunyai ketakutan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Artinya, mereka berani menghadapi risiko perlawanan dari pihak kompetitor. Yang dilupakan oleh para kandidat adalah bahwa segala tindak-tanduk mereka diketahui masyarakat dan sebagian menertawainya.
Kedua, boleh dikatakan salah satu atau keduanya mempersepsikan pemilihan sudah dekat. Ini menandakan kepanikan dari mereka. Padahal masih ada waktu tiga bulan untuk mempersiapkan diri. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka waktu tiga bulan ini lumayan cukup untuk menggelar berbagai program yang akan dilakukan.
Ketiga, bisa jadi mereka merasa kurang mampu menyusun rencana menghadapi kompetitor, sehingga mencari-cari kelemahan lawan yang tidak substantif bagi perhelatan perebutan calon presiden dan wakil presiden.
Sudah jamak dikatakan bahwa perdebatan paling pantas yang dilakukan oleh kandidat adalah soal program. Akan tetapi sebelum dibukanya perdebatan formal di televisi, maka secara etika masing-masing pihak tidak boleh menyerang kebijakan. Perdebatan antarkandidat haruslah dilakukan di televisi atau mungkin juga radio, karena masing-masing pihak akan mampu mempertahankan argumentasinya secara langsung.
Menyerang kelemahan lawan yang bukan substansi kampanye adalah membuang-buang waktu dan tenaga, lemah dan tidak etis. Membawa masalah ini ke Bawaslu, mungkin bukan ranahnya.
Maka yang terbaik adalah komentar dari masyarakat dan imbauan para tokoh. Masyarakat haruslah besuara agar kekeliruan para penasihat calon presiden ini tidak terulang lagi, dan para tokoh harus mendukung komentar masyarakat tersebut.
Masyarakat pada posisi seperti ini kelihatan lebih pintar dari penasihat calon presiden. Karena itulah maka dalam perjalanan ke depan masyarakat harus lebih mempelajari dengan teliti setiap ujaran yang diungkapkan oleh para calon. Ujaran ini memberi gambaran tentang bagaimana mereka sesungguhnya.
Dengan cara pandang seperti inilah nanti kita lihat perdebatan calon presiden dan wakil presiden di televisi pertengahan bulan Januari 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan bahwa pertanyaan dalam debat nanti akan diserahkan beberapa hari menjelang perdebatan.
Secara sosial ini akan lebih baik. Dari sisi kandidat akan dapat mempelajari pertanyaan dan membuat jawaban lebih komprehensif dengan data dukung yang kuat, juga dengan logika yang kuat untuk dipresentasikan kepada publik. Bagi masyarakat, akan tahu gambaran secara lebih komplit tentang penguasaan materi, data yang disampaikan, cara penyampaian sampai kekuatan tim sukses dan mentor yang ada di belakangnya.
Tetapi bagi masyarakat, akan mendapatkan suguhan lain lagi yang jauh lebih menarik. Komisi Pemilihan Umum telah mengatakan bahwa pertanyaan bebas juga akan muncul di televisi, yaitu pada saat kedua pasangan saling lempar pertanyaan.
Di sinilah akan terlihat bagaimana kemampuan dan kelihaian para kandidat untuk mempertahankan jawaban berdasarkan data yang dibuat sebelumnya. Atau malah mengimprovisasi jawaban berdasarkan data tersebut. Lebih menarik lagi kalau kandidat mampu mematahkan argumen data yang disajikan atau sekalian mematahkan pertanyaan yang diajukan. Bagi publik, kandidat yang mampu mematahkan pertanyaan memberikan hiburan dan kesegaran tersendiri untuk menontonnya.
Tugas masyarakat sekarang adalah melihat wacana tersebut. Gabungan ujaran itu akan menjadi wacana. Dan sambungan wacana inilah yang dapat diartikan, dapat diprediksi tentang bagaimana kelak ketika calon dan pasangan ini menjadi presiden. Dengan cara itulah kita, masyarakat akan mampu membuat perbandingan terhadap wacana-wacana dangkal yang muncul menjelang pemilihan presiden ini.
Intinya, jangan sia-siakan kesempatan untuk menonton perdebatan calon presiden dan wakil presiden di televisi nanti. Sudah lebih dari dua dekade Indonesia melakukan reformasi. Malu kepada generasi milenial yang lahir tahun 1998 dan setelahnya, apabila model-model kampanye dan ujaran politik Indonesia masih dangkal. Generasi itu sekarang sudah remaja dan jadi mahasiswa.












