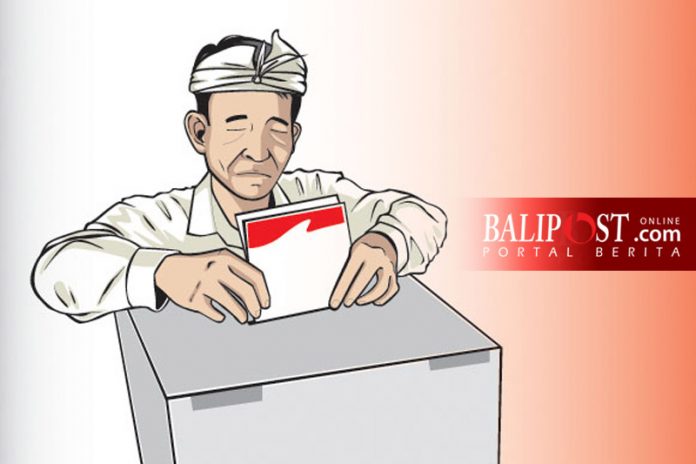
Oleh Ribut Lupiyanto
Partisipasi menjadi salah satu kunci kualitas demokrasi. Sayangnya angka partisipasi selalu dibayangi hantu demokrasi. Hantu abadi yang hadir dalam setiap kontestasi demokrasi adalah golongan putih (golput). Tidak terkecuali di Pemilu 2019 yang lalu. Golput menjadikan kontestan dan penyelenggara pemilu diselimuti rasa galau menghadapi pemilu.
Kontestan pemilu dirugikan terkait pengurangan potensi suara. Penyelenggara pemilu dirugikan terkait stigma negatif menyangkut kinerja lembaganya.
Partisipasi memang tidak memengaruhi legitimasi. Akan tetapi, berefek pada kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Golput penting dirunut akarnya hingga dapat ditempuh strategi mengakselerasi partisipasi ke depan. Golput menjadi momok bagi kualitas demokrasi. Partisipasi politik menunjukkan tren mengkhawatirkan selama pemilu pascareformasi.
Tingkat partisipasi Pemilu 1999 sebesar 92,74 persen, Pemilu 2004 sebesar 84,07 persen, Pemilu 2009 semakin turun menjadi 70,99 persen, dan membaik pada Pemilu 2014 sebesar 75,11 persen. KPU hanya mampu menargetkan partisipasi Pemilu 2019 sebesar 77,5 persen. Artinya, masih belum ada obsesi melampaui capaian Pemilu 2004. Angka pasti partisipasi Pemilu 2019 masih belum dapat diketahui, mengingat proses rekapitulasi suara belum usai.
Konstitusi Indonesia menempatkan partisipasi pemilu sebagai hak bukan kewajiban. Konsekuensinya golput menjadi bagian pilihan abstain yang legal. Golput menjadi tantangan bagi kontestan dan penyelenggara pemilu. Banyak kemungkinan yang menjadi akar penyebab golput. Pertama, golput sebagai ideologi.
Beberapa kelompok keagamaan menganggap pemilu sebagai produk demokrasi adalah haram atau najis. Kalangan antidemokrasi ini menjadikan golput sebagai kewajiban ideologis. Jumlah kalangan ini terbatas, tetapi loyal. Perubahan ideologis hampir mustahil dilakukan kecuali langsung melalui instruksi pucuk pimpinannya.
Kedua, golput sebagai pilihan idealisme. Pelaku golput jenis ini tidak memiliki identitas komunal, tetapi lebih bersifat individual. Hak memilih dikorbankan lantaran ketidaksesuaiannya dengan dinamika politik dan tingkah polah kontestan.
Generalisasi kerap dilakukan dengan menilai politik kotor, semua parpol korup, semua caleg melakukan politik uang, dan lainnya. Kalangan ini mendominasi pelaku golput karena lebih aktif menyatakan kekecewaan dan menginformasikan aib politik kepada publik. Mereka umumnya terjangkit apatisme dan apolitisme.
Ketiga, golput karena administratif. Administrasi kepemiluan selalu menghadapi permasalahan kompleks. Daftar pemilih pemilu tidak pernah beres dan terus berada pada posisi darurat. Karut-marut disebabkan validitas data yang rendah. Problem data terletak pada data ganda, masih tercantumnya penduduk meninggal, terdaftarnya TNI/Polri, nama tidak dikenal dan alamat tidak jelas, pemilih yang tidak ada pemilik atau tidak sesuai informasinya (ghost voters), serta warga yang belum terdaftar.
Ketidakvalidan daftar pemilih memicu peningkatan angka golput. Padahal, pemilih itu memang tidak ada. Warga yang tidak terdaftar juga terpaksa melakukan golput.
Keempat, golput akibat buta politik. Pelaku golput ini tidak memahami urgensi politik dan tidak mau tahu terhadap politik. Seorang penyair Jerman bernama Bertolt Brecht mengatakan bahwa buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik.
Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Kelima, golput karena situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang paling menentukan adalah saat hari pemungutan suara.
Pelaku golput ini kebanyakan warga yang sedang melakukan mobilitas antartempat. Regulasi mengatur perpindahan tempat pemungutan suara (TPS) dengan birokrasi berbelit, seperti harus meminta formulir pindah. Hal ini akan sulit dilakukan bagi mereka yang bepergian mendadak atau malas mengurus perpindahan TPS.
Politik di Indonesia secara strategis mengandung dua unsur, yaitu kepemimpinan nasional dan partisipasi masyarakat (Lemhanas, 1975). Pemilu merupakan agenda suksesi politik yang akan menentukan nasib bangsa ke depan. Perubahan mustahil akan terwujud tanpa adanya semangat demokratisasi melalui partisipasi masyarakat.
Persepsi politik masyarakat di negara berkembang cenderung dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penduduk, pendidikan, jenis kelamin, unsur primordial daerah, dan perbedaan nilai-nilai tradisional (Rush, 1983). Rachmawati (2003) mengemukakan partisipasi memiliki empat level, yaitu berbagi informasi (information sharing), konsultasi (consultation), pembuatan keputusan (desicion making), serta memprakarsai tindakan (initiating action). Partisipasi yang ideal merupakan proses kontinu. Pemberdayaan politik mesti diimplementasikan mulai dari pra, saat, dan pasca-pemilu secara berkelanjutan.
Golput menjadi tantangan yang mesti ditekan demi peningkatan partisipasi. Golput dapat ditekan melalui pendidikan politik, akomodasi regulasi, dan perbaikan administrasi data. Pendekatan spesifik penting dibedakan sesuai akar golput di atas. Penekanan angka golput juga hendaknya bersifat prioritatif. Pertama, dengan pendidikan politik.
Pendidikan politik dapat dilakukan terhadap pelaku golput karena buta politik dan idealisme. Kalangan buta politik dapat dididik mengenai urgensi politik bagi pembangunan bangsa. Pemahaman juga penting ditanamkan bahwa semua penduduk berkepentingan terhadap politik karena semua urusan negara diselenggarakan melalui kebijakan politik. Kalangan ini dapat didorong untuk aktif memberikan aspirasi agar kepentingannya terakomodasi secara politis.
Pelaku golput idealis lebih membutuhkan waktu lama melalui diskusi dan peyakinan. Kontestan politik penting meyakinkan kepada mereka dengan gagasan dan program ke depan. Kalangan ini mesti dicerahkan bahwa tidak sepenuhnya politik kotor dan tidak semua politisi busuk. Mereka dapat memilih yang buruk dari yang paling buruk.
Kedua, melalui akomodasi regulasi. Regulasi kepemiluan hendaknya mengedepankan kemudahan demi kepentingan demokrasi. KPU layak mempertimbangkan terobosan pengaturan bahwa pemilih dapat memilih meski belum memiliki e-KTP pada hari pencoblosan. Selain itu juga penting mempermudah syarat pindah lokasi pemilihan TPS.
Tanggung jawab menekan golput sebagai penghalang partisipasi politik berada di pundak semua komponen. Kontestan pemilu penting ambil bagian sekaligus dalam rangka menambah suara. Penyelenggara pemilu mesti bertanggung jawab demi membuktikan kinerjanya. Pemerintah juga penting membantu demi penguatan legitimasi dan kepercayaan publik dalam pembangunan. Sinergisme antarpihak akan memudahkan pencapaian partisipasi pemilu dan kontestasi demokrasi lain ke depannya.
Penulis, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)












