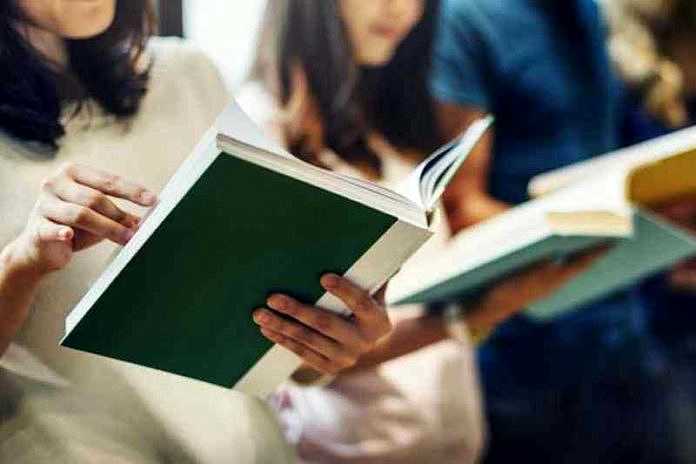
Oleh I Ketut Serawan
Kegiatan literasi mulai menggeliat di sekolah-sekolah. Geliat ini bermula dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) per tahun 2016 sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Konkretnya, para siswa diwajibkan membaca buku non-mapel setiap hari 15 menit sebelum pembelajaran dimulai di kelas.
Walaupun singkat, pembiasaan tersebut cukup membangunkan kesadaran siswa dari belenggu budaya ‘’kontrak literasi’’ yang sudah mendarah daging pada diri siswa. Budaya ‘’kontrak literasi’’ merupakan aktivitas belajar (membaca-menulis) untuk memperoleh (jangka pendek) apresiasi nilai atau angka.
Keinginan memperoleh angka-angka inilah yang mendorong siswa untuk belajar. Itulah sebabnya, siswa baru belajar apabila ada tes ulangan atau ujian. Mereka belajar untuk mendapatkan angka yang baik. Selanjutnya, angka-angka ini didokumentasikan dalam rapor atau ijazah untuk dibanggakan di kemudian hari.
Segi kepraktisan atau efek ilmu yang dipelajari dari aktivitas belajar, tidak menjadi persoalan. Habis belajar dan siswa memperoleh angka, maka kontrak sudah berakhir. Apakah ilmu yang dipelajari berguna atau tidak dalam kehidupan sehari-hari? Tidak penting.
Belajar menjadi semacam proyek (kontrak). Kontrak untuk menjawab soal-soal sesaat. Setelah menghadapi ulangan atau ujian, siswa merasa bebas. Mereka merasa bebas dari aktivitas belajar (membaca/menulis). Membaca pasca-tes dianggap tindakan sia-sia.
Selanjutnya, dari ‘’kontrak literasi’’ inilah menumbuhkan anggapan bahwa belajar (membaca) dikhususkan untuk status siswa atau mahasiswa. Istilah belajar adalah kontrak ketika menjadi siswa atau mahasiswa.
Lepas dari dua status ini, berarti bebas dari aktivitas membaca dan menulis. Oleh karena itu, banyak masyarakat (orangtua) merasa tak berdosa ketika menyuruh anaknya belajar.
Para orangtua sering menceramahi, memaksa, memarahi, mengancam, hingga pasrah. Karena beberapa anak malah memilih diam menutup pintu, lalu komunikasi menjadi buntu. Mereka mengurung diri di kamar entah untuk kondisi ancaman belajar atau pura-pura belajar.
Daripada kukuh merasa benar dan menjadikan anak sebagai ‘’pesakitan belajar’’, lebih baik orangtua menjadi panutan literasi di rumah. Orangtua membiasakan diri membaca di rumah. Berusaha terus menjadi contoh pembaca yang baik di keluarga.
Lakukan berulang-ulang. Setiap saat. Kalau bisa setiap hari. Karena sesungguhnya anak membutuhkan contoh-contoh konkret di lingkungan keluarga.
Apa yang sering dilihatnya, dialaminya, dan dirasakannya di rumah akan membentuk kebiasaan pada diri siswa. Di sinilah, pentingnya orangtua tampil menjadi contoh bukan sekadar memberikan contoh-contoh. Orangtua harus bisa menjadi panutan literasi di rumah.
Begitu juga di lingkungan sekolah. Guru harus dapat menjadi panutan literasi bagi anak didiknya. Namun kenyataannya, kadangkala guru gagal menjadi teladan. Mereka meminta para siswa rajin dan tekun belajar.
Pun ketika siswa membaca 15 menit sebelum pembelajaran di kelas. Semangatnya bak juru kampanye. Suara para guru lantang. Sayangnya, guru lebih sering memanfaatkan waktu senggang untuk ngerumpi di ruang guru. Mereka enggan meng-upgrade diri dengan membaca (walaupun tidak semua). Beberapa guru merasa nyaman dengan ilmu yang serba-berkecukupan sewaktu di bangku kuliah.
Kontrak literasi yang membudaya, menyebabkan ortu atau guru sering gagal menjadi panutan. Celakanya, sering ortu dan guru tetap merasa benar. Mereka membela diri dengan alasan faktor usia, kesibukan, lelah dan lain sebagainya. Alasan ini seolah-olah sudah menjadi legitimasi bahwa usia tua harus dibebaskan dari aktivitas belajar.
Sejujurnya, literasi merupakan budaya baru bagi masyarakat. Ia baru menggema di tengah kuatnya pengaruh tradisi lisan dalam masyarakat. Bahkan, usianya tidak tanggung-tanggung. Sudah berabad-abad lalu. Masyarakat kita besar dari polarisasi penutur (kemampuan berbicara) dan pendengar (kemampuan menyimak).
Jadi, untuk mengalihkan budaya lisan ke budaya belajar (baca-tulis), dibutuhkan proses dan kemampuan adaptasi yang baik. Semakin tinggi kemampuan adaptasi kita, maka semakin cepat dapat menyesuaikan diri dengan budaya literasi.
Sebaliknya, semakin rendah maka budaya literasi kita bergerak lambat. Ortu/guru merupakan korban hegemoni trans budaya lisan. Mereka lahir dari lingkungan dominasi tradisi lisan yang begitu kuat dan (dengan) perspektif membaca sebagai kontrak literasi.
Ditambah dengan kemampuan adaptasi yang minim, maka wajar ortu/guru belum mampu menjadi panutan literasi. Meskipun demikian, tidak semua ortu/guru (old) digolongkan sebagai generasi minus literasi. Ada beberapa ortu/guru (old) yang memiliki kemampuan adaptasi literasi yang tinggi, sehingga mereka tetap tampil sebagai panutan berliterasi. Namun, jumlahnya sangat sedikit.
Panutan Literasi
Saat ini, anak-anak membutuhkan panutan literasi terutama di keluarga. Keluarga sangat efektif dalam membentuk karakter anak. Lingkungan keluargalah yang paling banyak menyita waktu anak-anak. Keluarga juga menjadi lingkungan pribadi (psikologi) yang paling dekat dan akrab. Bibit karakter bermula dari lingkungan keluarga.
Keseharian di keluarga akan otomatis membentuk nilai (karakter) termasuk kebiasaan literasi. Jika ortu dapat menciptakan iklim literasi yang kondusif di rumah, maka anak-anak relatif lebih mudah tertular virus literasi. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi ortu kecuali berusaha membiasakan diri menjadi contoh literasi di keluarga.
Karakter literasi yang tumbuh di keluarga akan memudahkan budaya baca-tulis anak berkembang di sekolah. Dengan catatan, sekolah harus mendorong iklim literasi yang baik, terutama mulai dari guru.
Guru harus menjadi model/panutan literasi dengan memanfaatkan waktu untuk membaca dan menulis. Selain itu, sekolah dapat menjadi fasilitator literasi dengan menyediakan bahan bacaan (tulis) baik cetak, digital, dan lain sebagainya.
Pembelajaran literasi mirip dengan pembelajaran agama dan budi pekerti. Mapel ini dimasukkan dalam kokurikuler dan diajarkan secara rutin di sekolah. Namun, hasilnya dianggap mengecewakan.
Etika dan moral generasi muda kita dikatakan tumbuh tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Pun generasi tuanya. Salah satu indikatornya ialah menjamurnya budaya korupsi di segala sektor justru ketika mapel ini digemakan di sekolah-sekolah.
Metodologi dituding sebagai salah satu faktor kekurangoptimalan pembelajaran agama dan budi pekerti. Publik menilai bahwa pembelajarannya masih menggunakan metodologi konvensional.
Sekolah membelajarkan mapel ini sebagai ‘’proyek penghabisan materi’’. Hasilnya, tentu teoretis, bukan unjuk keterampilan berbuat baik—dengan panutan di sekelilingnya. Akibatnya, anak-anak tumbuh dengan baik hanya pada kemampuan kognitif (konsep) moralnya, tetapi miskin pada tataran implementasinya. Ditambah lagi, lingkungan sosial yang cenderung kurang baik, karena dominan memamerkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan teori moral.
Penumbuhan (pembiasaan) literasi juga sama. Dia tidak cukup diintegrasikan dalam mapel dan berakhir dengan angka-angka. Dia harus terus distimulus dan dibiasakan oleh pihak sekolah (guru) dengan menjadi panutan utama.
Untuk mengikat guru menjadi panutan literasi, barangkali diperlukan tuntutan administrasi. Misalnya, dengan memasukkan bukti fisik literasi sebagai kelengkapan administrasi dalam kenaikan pangkat/golongan. Persyaratan administratif ini akan mendorong guru untuk terus membaca. Lama-kelamaan, diharapkan dapat menulis buku dan dijadikan stimulus berkarya (literasi) kepada siswa.
Gerakan literasi juga dapat digemakan di sekolah-sekolah dengan menggelar acara-acara yang berbau literasi. Misalnya, sekolah menyelenggarakan pameran literasi, seminar, dan bedah buku dengan mengundang ortu siswa sebagai pesertanya. Partisipasi ortu ini diharapkan dapat menyadarkan mereka melek dan menjadi panutan literasi di keluarga. Di tangan ortu yang melek inilah, mimpi berliterasi anak bisa terwujud.
Penulis, guru bahasa dan sastra Indonesia di SMP Cipta Dharma Denpasar












