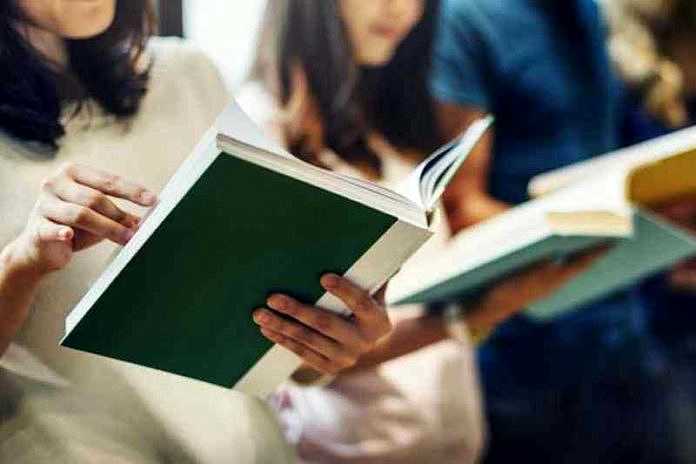
Bali boleh bangga dengan khazanah sastranya yang adiluhung dan beragam. Namun, jangan berheni di sana, karena ternyata sastra Bali banyak ditulis dalam huruf Bali dan belum diterjemahkan. Sementara kita tahu, budaya masyarakat Bali sangat hati-hati membuka karya sastra kuno dengan cara instan.
Ketika belajar huruf Bali pun masih ada ancaman. Bisa gila akibatnya, demikian pameo di masyarakat. Kondisi ini yang membuat banyak karya sastra Bali tak terjamah oleh masyarakatnya. Mungkin ini ‘’politik’’ oknum tertentu guna memonopoli keilmuan. Atau bisa jadi sengaja dibuat demikian agar generasi muda kita tertantang untuk menembus batas-batas tersebut.
Apalagi ada mitos bisa ‘’gila’’ akibatnya. Hal ini paradoks dengan tuntutan zaman sekarang kita mestinya ‘’gila’’ membaca. Hal ini harus didahului dengan kesenangan belajar bahasa dan huruf Bali.
Tanpa landasan itu, kita tak mungkin membaca lontar dan sastra Bali dengan baik. Kini tantangan baru muncul bagi guru bahasa Bali kita, bagaimana membuat anak-anak gemar dan cerdas menulis aksara Bali.
Tanpa alat ini, kita tak mungkin bisa membaca. Fakta di lapangan, membaca dengan huruf Bali di sekolah oleh anak-anak hanya dipakai sebatas mencari nilai saat ulangan semester saja, belum berkelanjutan. Makanya untuk menanamkan budaya ‘’gila’’ membaca aksara Bali bisa terhambat.
Secara umum, budaya membaca remaja kita patut dipertanyakan. Kita lihat saja sehari-hari di rumah saat liburan panjang sekolah yang sedang berlangsung. Mereka lebih memilih chatting di medsos ketimbang membaca buku. Apalagi buku pelajaran.
Literasi belum menjadi budaya mereka. Untuk menjadikan membaca sebagai sebuah budaya haruslah dimulai dari pembiasaan dan pembiasaan secara kontinu.
Kita bisa lihat saja aktivitas dan cara belajar pelajar sekarang. Mereka tak mau membaca materi di buku terlebih dahulu untuk memperoleh pengalaman baru atau materi baru, namun sudah loncat menjawab pertanyaan di bagian akhir materi.
Namun anehnya, mereka belum menemukan jawaban langsung minta bantuan medsos. Bukan membuat mereka merasa tertantang mencari jawaban dengan cara membaca materi pelajaran.
Salahnya guru juga yang semakin jarang memberi tugas aplikated bagi siswanya dalam soal-soal problem solving. Makanya jangan heran anak-anak di SMA banyak yang mengeluh bahwa gurunya hanya hadir pada awal pelajaran dengan alasan Children Centre Learning (CSL) kemudian meninggalkan kelas tanpa pengawasan bagaimana proses siswa mendapatkan jawaban. Beda dengan terdahulu, guru mengawasi siswanya mencari bahan di perpustakaan dan memberi arahan buku mana yang harus dibaca untuk referensi masalah tertentu.
Kini, adanya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) patut dijadikan momentum guna meningkatkan minat baca anak muda. Namun sayang, dengan sistem zonasi dan PPDB gelombang II yang mewajibkan SMP dan SMA-SMK negeri menerima siswa maksimal dan diterjemahkan lain oleh pelaksana di bawah membuat semua ruang perpustakaan dan lab sekolah disulap menjadi ruang kelas.
Buku-buku tak ada tempat lagi dipajang di ruangan bahkan alat lab disimpan rapat alias dimatikan. Semua demi politik dan popularitas. Ini tantangan baru Bali untuk menanamkan budaya mari ‘’gila’’ membaca.
Bisa-bisa medsos makin melesat dengan cengkeraman pengaruh negatifnya. Semua ini harus kita sikapi, bukan dibiarkan. Pemerintah sebagai penanggung jawab program GLS mestinya taat juga dengan aturan bahkan mendukung GLS. Bukan sebaliknya membunuh budaya ‘’gila’’ membaca dengan mematikan aspek pendukungnya.












